Buku Bahasa Indonesia Karen Amstrong: Sejarah Tuhan
Dalam ajaran Weda, orang mengalami kekuatan suci dalam ritual pengurbanan. Mereka menyebut kekuatan suci ini Brahman. Kasta para rahib (disebut dengan istilah Brahmana) juga diyakini mempunyai kekuatan ini. Karena ritual pengurbanan dipandang sebagai mikrokosmos alam semesta, Brahman lambat laun diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyangga segala sesuatu. Seluruh dunia dipandang sebagai aktivitas ilahi yang menyeruak dari wujud misterius Brahman, yang merupakan makna batin seluruh eksistensi. Upanishads mendorong orang untuk menumbuhkan rasa kehadiran Brahman di dalam segala sesuatu. Ini adalah proses pewahyuan dalam makna harfiahnya: pengungkapan dasar tersembunyi dari seluruh wujud. Segala sesuatu yang terjadi merupakan manifestasi Brahman: pandangan yang benar terletak dalam persepsi kesatuan di balik fenomena yang berbeda. Sebagian Upanishads melihat Brahman sebagai kekuatan pribadi, tetapi sebagian lain melihatnya betul-betul impersonal. Brahman tidak dapat dipanggil dengan kata "engkau"; ini adalah istilah yang netral, bukan laki-laki atau perempuan, bukan pula dia dialami sebagai kehendak ilah yang berdaulat. Brahman tidak berbicara kepada manusia. Dia tak dapat bertemu dengan lelaki atau perempuan; dia berada di atas segala aktivitas manusia. Dia juga tidak menanggapi kita dengan secara personal; dosa tidak membuatnya "marah", dan dia tidak dapat dikatakan "mencintai" atau "membenci" kita. Bersyukur atau memujinya karena telah menciptakan dunia sama sekali tidak tepat.
Kekuatan ilahiah ini akan betul-betul terasing dari kita seandainya tidak ada fakta bahwa ia melingkupi, menyokong, dan mengilhami kita. Teknik-teknik Yoga telah membuat orang sadar tentang dunia batin. Disiplin pengaturan postur, cara bernapas, makanan, dan konsentrasi mental ini juga telah berkembang secara mandiri dalam kebudayaan lain, seperti akan kita lihat nanti, dan tampaknya menghasilkan pencerahan serta iluminasi yang telah ditafsirkan secara berbeda-beda, namun alamiah bagi kemanusiaan. Upanishads mengklaim bahwa pengalaman mengenai dimensi baru dari diri ini merupakan kekuatan suci yang sama dengan yang melingkupi seluruh alam. Prinsip abadi yang ada dalam setiap individu disebut Atman: ini 60 Pada Mulanya ... merupakan versi baru visi holistik paganisme kuno, penemuan kembali dalam terma baru Satu Kehidupan yang ada di dalam dan di luar diri kita yang pada dasarnya bersifat sakral. Chandogya Upanishads menjelaskan hal ini melalui analogi tentang garam. Seorang pemuda bernama Sretaketu telah mempelajari Weda selama dua belas tahun dan merasa telah cukup menguasainya. Ayahnya, Uddalaka, mengajukan sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawabnya. Kemudian ayahnya mengajarkan tentang kebenaran fundamental yang sama sekali belum diketahuinya. Dia memerintahkan anaknya untuk meletakkan sepotong garam di dalam air dan melaporkan hasilnya pada pagi hari berikutnya. Ketika sang ayah memintanya untuk mengambil garam itu, Sretaketu tidak dapat menemukannya karena garam itu telah larut semuanya. Uddalaka mulai bertanya:
"Maukah engkau mencicipi bagian ini? Seperti apa rasanya?" katanya. "Garam." "Cicipilah bagian tengahnya. Seperti apa?" "Garam." "Cicipilah bagian ujungnya. Seperti apa?" "Garam." "Buanglah itu dan mendekatlah kepadaku." Sretaketu melakukan apa yang diperintahkan, namun [itu tidak membuat garam] menjadi berubah. [Ayahnya berkata]: "Anakku, memang benar bahwa engkau tidak bisa melihat Wujud ada di sini, namun wujud itu benar-benar ada di sini. Esensi pertama ini—dimiliki alam semesta sebagai Dirinya: Itulah yang Nyata: Itulah Diri: itulah engkau, Sretaketu!"
Jadi, meskipun kita tidak dapat melihatnya, Brahman melingkupi dunia dan, sebagaimana Atman, abadi dalam diri setiap kita.28 Atman mencegah pemberhalaan Tuhan, menjadi Realitas eksterior "di luar sana", proyeksi ketakutan dan keinginan kita sendiri. Dalam Hinduisme, Tuhan tidak dilihat sebagai sebuah Wujud yang ditambahkan ke dunia seperti yang kita ketahui, karena itu tidak pula identik dengan dunia. Tak bisa kita memahami ini melalui akal semata. Pemahaman ini "diwahyukan" kepada kita melalui pengalaman (anubhara) yang tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata atau konsep. Brahman adalah "Apa yang tidak bisa diucapkan dalam kata-kata, tetapi sesuatu yang dengannya kata-kata diucapkan ...
Apa yang tak bisa dipikirkan oleh akal, tetapi sesuatu yang dengannya akal berpikir."29 Mustahil untuk berbicara kepada Tuhan yang semelekat ini atau berpikir mengenai dia, menjadikannya objek pikiran semata. la adalah Realitas yang hanya bisa dicerna dalam puncak perasaan orisinal yang melampaui kesadaran diri: Tuhan
datang kepada pikiran orang-orang yang mengenai Dia melampaui pikiran, bukan kepada mereka yang membayangkan Dia bisa diraih oleh pikiran. Dia tidak dikenal oleh kaum cendekia dan dikenal oleh orang sederhana. Dia dikenal di dalam puncak keterjagaan yang membukakan pintu kehidupan abadi
Sebagaimana terhadap dewa-dewa, nalar tidak disangkal tetapi dilampaui. Pengalaman tentang Brahman atau Atman tidak dapat dijelaskan secara rasional, seperti halnya sepenggal musik atau syair. Akal mutlak diperlukan untuk menciptakan karya seni semacam itu dan mengapresiasinya, tetapi ia menawarkan sebuah pengalaman yang melampaui daya otak atau akal murni. Ini juga akan menjadi tema konstan dalam sejarah Tuhan
Cita-cita transendensi personal juga bersemayam di dalam diri Yogi, orang yang meninggalkan keluarganya dan melepaskan diri dari keterkaitan dan tanggung jawab sosial demi mencari pencerahan, meletakkan dirinya di dalam realitas wujud yang lain. Sekitar 538 SM, seorang pemuda bernama Siddharta Gautama juga meninggalkan istrinya yang cantik, putranya, rumahnya yang mewah di Kapilawastu, kira-kira 100 mil ke arah utara Benares, dan menjadi seorang petapa sederhana. Dia terhenyak melihat penderitaan manusia dan bermaksud menemukan rahasia untuk mengakhiri nestapa yang dilihatnya ada dalam segala sesuatu di sekelilingnya. Selama enam tahun, dia duduk di kaki para guru spiritual Hindu dan menjalani tirakat penyangkalan diri yang berat, tetapi tidak banyak membuat kemajuan. Ajaran para guru itu tidak menarik hatinya, dan penyiksaan diri hanya membuatnya lemah. Baru setelah meninggalkan metode-metode ini sama sekali dan mengalami ketidaksadaran pada suatu malam dia pun mendapatkan pencerahan. Seluruh kosmos bersorak, bumi berguncang, bunga-bunga bertebaran dari langit, angin semerbak berembus, dan para dewa dari berbagai tingkatan langit bersukaria.
Kembali, seperti dalam visi pagan, para dewa, alam, dan manusia bersatu dalam simpati. Ada harapan baru untuk membebaskan diri 62 Pada Mulanya ... dari penderitaan dan mendapatkan nirvana, akhir semua nestapa. Gautama telah menjadi Buddha, Yang Tercerahkan. Pada mulanya, setan Mara menggodanya untuk tetap berada di tempat itu dan menikmati anugerah yang baru didapatkannya: tak ada gunanya upaya menyebarkan berita itu karena tak seorang pun akan mempercayainya. Namun, dua dewa dari kuil tradisional—Maha Brahma dan Sakra, Tuan para devas—datang menemui Buddha dan memintanya untuk menjelaskan metodenya kepada dunia. Buddha setuju dan selama empat puluh tahun ke depan, dia mengembara ke pelosok India untuk menyampaikan pesannya: dalam dunia yang penuh derita ini, hanya satu yang tidak berubah. Itulah Dharma, cara hidup yang benar, satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari penderitaan
Ini tak ada hubungannya dengan Tuhan. Secara implisit, Buddha mempercayai eksistensi dewa-dewa sebab mereka merupakan bagian dari latar kulturalnya, namun dia tidak percaya bahwa mereka bermanfaat banyak bagi manusia. Mereka pun terikat dalam realitas penderitaan dan perubahan; mereka tidak membantunya meraih pencerahan; mereka terlibat dalam siklus kelahiran kembali sebagaimana makhluk lain, dan akhirnya mereka juga akan sirna. Akan tetapi, pada saat yang krusial dalam kehidupannya—seperti ketika dia memutuskan untuk menyebarkan pesannya—dia membayangkan para dewa mempengaruhinya dan memainkan peran aktif. Oleh karena itu, Buddha tidak menyangkal dewa-dewa, tetapi percaya bahwa Realitas tertinggi nirvana lebih luhur daripada para dewa. Ketika orang Buddha mengalami kedamaian atau rasa transendensi dalam meditasi, mereka tidak mempercayai bahwa itu berasal dari hubungan dengan wujud yang supranatural. Keadaan seperti itu alamiah bagi kemanusiaan: bisa dicapai oleh setiap orang yang hidup dengan cara yang benar dan mempelajari teknik Yoga. Oleh sebab itu, alih-alih bersandar kepada suatu dewa, Buddha mengajak murid-muridnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.
Ketika bertemu murid pertamanya di Benares setelah peristiwa pencerahannya, Buddha memaparkan sistemnya yang didasari oleh satu fakta esensial: seluruh eksistensi adalah dukkha. Semuanya terdiri dari penderitaan: seluruh kehidupan adalah suram. Segalanya datang dan pergi dalam perubahan tak bermakna. Tak ada yang mempunyai arti penting yang permanen. Agama dimulai dengan persepsi bahwa ada sesuatu yang salah. Di masa pagan kuno, ada mitos tentang dunia arketipal suci, yang bersesuaian dengan dunia kita dan bisa menanamkan kekuatannya kepada manusia. Buddha mengajarkan bahwa adalah mungkin untuk melepaskan din dan dukkha melalui cara hidup yang penyayang terhadap sesama makhluk, berbicara dan bertindak lemah lembut, ramah, dan benar, serta menjauhkan diri dari segala obat-obatan atau bahan memabukkan yang bisa mengaburkan pikiran. Buddha tidak mengklaim telah menciptakan sistem ini. Dia bersikeras bahwa dia hanya "memperoleh" saja: "Aku telah melihat ajaran kuno, sebuah Jalan kuno, yang ditelusuri Buddha dari zaman yang lalu Seperti undang-undang paganisme, Buddhisme juga dibatasi oleh struktur eksistensi dasar, yang melekat dalam kondisi kehidupan itu sendiri. la mempunyai realitas objektif bukan karena ia dapat diperlihatkan melalui bukti logis, melainkan karena setiap orang yang secara serius berusaha untuk hidup dengan cara itu akan menemukan bahwa sistem itu ternyata efektif. Keefektifannya, bukan bukti filosofis atau historis, selalu menjadi ciri khas agama yang berhasil. Selama berabad-abad orang Buddha di banyak belahan bumi telah merasakan bahwa gaya hidup ini menghasilkan pengertian tentang makna transendensi.
Karma mengikat manusia kepada lingkaran kebangkitan kembali tak berujung dalam rangkaian kehidupan yang sarat derita. Namun jika mereka mampu mengubah perilaku egois mereka, mereka akan mampu mengubah nasib. Buddha membandingkan proses kelahiran kembali ini dengan api yang menyulut sebuah lampu, yang darinya nyala api lampu kedua berasal, demikian seterusnya hingga nyala itu padam. Jika seseorang masih menyala dengan dosanya pada saat dia mati, maka dia akan menyulut lampu yang lain. Akan tetapi, jika api itu dipadamkan, lingkaran penderitaan akan berhenti dan nirvana akan diperoleh. "Nirvana" secara harfiah berarti "padam" atau "usai". Ini bukan semata-mata sebuah keadaan negatif. Di kalangan orang Buddha, ia justru memainkan peran yang sebanding dengan Tuhan. Seperti dijelaskan Edward Conze dalam Buddhism: its Essence and Development, kaum Buddhis sering menggunakan penggambaran teistik untuk menjelaskan nirvana, realitas tertinggi:
Kami diajarkan bahwa nirvana itu permanen, stabil, abadi, diam, tak lapuk oleh usia, tak pernah mati, tidak dilahirkan, dan tidak diciptakan, bahwa ia adalah kekuatan, anugerah, dan kebahagiaan, perlindungan yang aman, tempat berteduh, dan tempat dengan rasa aman yang tak terpunahkan; bahwa ia adalah Kebenaran sejati dan Realitas tertinggi; bahwa ia adalah kebaikan, tujuan puncak, dan satu-satunya dambaan kehidupan kita, kedamaian yang abadi, terselubung, dan tak terpahami.
Beberapa penganut Buddha mungkin berkeberatan atas pembandingan ini karena mereka merasa konsep tentang "Tuhan" begitu terbatas untuk dapat menuangkan konsepsi mereka tentang realitas tertinggi. Umumnya hal ini disebabkan karena kaum teistik menggunakan kata "Tuhan" secara terbatas untuk merujuk kepada wujud yang terlalu berbeda dari kita. Sebagaimana para guru Upanishads, Buddha mengajarkan bahwa nirvana tidak bisa didefinisikan atau didiskusikan seakan-akan ia berbeda dari realitas manusia. Mencapai nirvana tidak sama dengan "naik ke langit" seperti yang sering dipahami orang Kristen. Buddha selalu menolak untuk menjawab pertanyaan tentang nirvana atau tentang hal-hal luhur lainnya karena pertanyaan semacam itu "tidak layak" dan "tidak pantas". Kita tidak bisa mendefinisikan nirvana karena kata-kata dan konsep kita terbelenggu oleh dunia indriawi dan perubahan. Pengalaman adalah satu-satunya "bukti" yang terandalkan. Muridmuridnya akan mengetahui bahwa nirvana ada hanya karena latihan mereka menjalani kehidupan yang baik akan memampukan mereka melihatnya.
Wahai para rahib, ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, tak tersusun. Jika, wahai para rahib, tidak ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, dan tak tersusun ini, maka tentu tak akan ada jalan keluar bagi yang dilahirkan, yang menjadi, yang diciptakan, yang tersusun. Tetapi karena ada yang tak dilahirkan, yang tak menjadi, yang tak diciptakan, dan yang tak tersusun, maka ada jalan keluar bagi yang dilahirkan, yang menjadi, yang diciptakan, dan yang tersusun
Para rahibnya tidak boleh berspekulasi tentang hakikat nirvana. Yang dapat dilakukan Buddha hanyalah menyediakan bagi mereka rakit yang akan membawa mereka menyeberang ke "pantai yang lebih jauh". Ketika ditanya apakah seorang Buddha yang telah mencapai nirvana tetap hidup setelah mati, dia mengabaikan pertanyaan ini karena menganggapnya "tidak layak". Sama tidak layaknya seperti menanyakan ke mana perginya api setelah ia "padam". Sama kelirunya mengatakan bahwa seorang Buddha yang hidup dalam nirvana berarti
tidak ada: kata "ada" tidak berhubungan dengan keadaan apa pun yang bisa kita pahami. Kita akan menemukan bahwa selama berabadabad, orang Yahudi, Kristen, dan Muslim telah memberikan jawaban yang sama terhadap pertanyaan tentang "keberadaan" Tuhan. Buddha berusaha memperlihatkan bahwa bahasa tidak mampu membahas realitas yang berada di luar jangkauan konsep dan akal. Lagi-lagi, dia tidak menolak akal tetapi menekankan arti penting pemikiran yang jernih serta akurat dan penggunaan bahasa. Namun akhirnya, dia berpendapat bahwa teologi atau kepercayaan seseorang, seperti ritual yang dijalaninya, tidaklah penting. Hal-hal seperti itu memang menarik, tetapi tidak punya arti final. Satu-satunya yang berharga adalah hidup dengan cara yang baik; jika ini diupayakan, penganut Buddha akan menemukan bahwa Dharma itu benar, meskipun mereka tidak bisa menyampaikannya dalam ungkapan yang logis.
Di sisi lain, orang-orang Yunani amat tertarik kepada logika dan nalar. Plato (kl. 428-348 SM) selalu menyibukkan diri mengkaji persoalan-persoalan epistemologi dan hakikat kebijaksanaan. Banyak karya awalnya ditujukan sebagai upaya membela Sokrates, yang mendesak orang untuk memperjelas gagasan mereka lewat pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukannya. Akan tetapi, Sokrates dihukum mati pada 399 SM dengan tuduhan merusak para pemuda dan murtad. Dalam cara yang tidak berbeda dengan yang ditempuh orang India, Plato kecewa terhadap upacara-upacara kuno dan mitosmitos agama yang menurutnya merendahkan dan tidak layak. Plato juga telah dipengaruhi filosof abad keenam SM, Pythagoras yang mungkin sekali telah terpengaruh gagasan-gagasan dari India, yang menyebar melalui Persia dan Mesir. Dia juga percaya bahwa jiwa adalah bagian zat ilahi yang terjatuh, tercemar, dan terperangkap dalam tubuh seperti dalam sebuah kuburan dan terhukum untuk menjalani siklus kelahiran kembali yang tiada habisnya. Dia telah menyuarakan pengalaman semua manusia tentang rasa keterasingan di dunia yang tampaknya bukan merupakan unsur sejati kita. Phytagoras mengajarkan bahwa jiwa bisa dibebaskan melalui penyucian ritual, yang akan memampukan manusia mencapai harmoni dengan semesta yang teratur. Plato juga meyakini eksistensi realitas suci dan tak berubah yang melampaui dunia indriawi, bahwa jiwa adalah sepenggal keilahian, unsur yang terlepas darinya, terpenjara dalam tubuh tetapi mampu meraih kembali status keilahiannya dengan cara penyucian daya nalar pikiran. Dalam mitos gua yang populer, Plato melukiskan kegelapan dan keburaman kehidupan manusia di bumi: manusia hanya mampu melihat bayang-bayang realitas abadi yang terpantul di dinding gua. Namun, lambat laun manusia mampu keluar lalu mencapai pencerahan dan pembebasan dengan melatih pikirannya memperoleh cahaya ilahi.
Pada akhir hayatnya, Plato mungkin telah meninggalkan doktrinnya tentang bentuk-bentuk atau ide-ide abadi, tetapi gagasan ini justru menjadi krusial bagi banyak monoteis ketika mereka berupaya mengungkapkan konsepsi ketuhanan mereka. Ide merupakan realitas stabil dan konstan yang bisa dipahami oleh kekuatan nalar, juga merupakan realitas yang lebih utuh, permanen, dan efektif dibandingkan fenomena material yang lemah dan selalu berubah yang kita capai lewat indra. Segala yang ada di dunia ini hanyalah pantulan, "bagian" atau "tiruan" dari bentuk-bentuk abadi di wilayah ilahi. Ada ide yang selalu bersesuaian dengan setiap konsepsi umum yang kita miliki, seperti Cinta, Keadilan, dan Keindahan. Akan tetapi, yang paling tinggi di antara semua bentuk adalah ide tentang Kebaikan. Dengan demikian, Plato telah memberi kerangka filosofis bagi mitos kuno tentang dunia arketipal. Gagasannya tentang keabadian dapat dilihat sebagai versi rasional dari alam suci mitis, yang di dalamnya hal-hal jasadiah menjadi bayang-bayang semata. Dia tidak membahas hakikat Tuhan, tetapi membatasi diri pada alam suci bentuk-bentuk, meski terkadang tampak bahwa Keindahan atau Kebaikan ideal tidak mewakili suatu realitas puncak. Plato yakin bahwa alam ilahiah itu statis dan tak berubah. Orang Yunani memandang gerak dan perubahan sebagai ciri realitas inferior: sesuatu yang memiliki identitas sejati selalu sama, dicirikan oleh ketetapan dan ketakberubahan. Dengan demikian, gerak yang paling sempurna adalah gerak melingkar karena ia terus-menerus berputar dan kembali ke posisi asalnya: gerak melingkar benda-benda langit meniru gerakan alam ilahiah dengan sebaik mungkin. Citra statis alam ilahiah ini akan berpengaruh sangat besar terhadap orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, walaupun hal itu sangat berbeda dengan Tuhan pemberi wahyu, yang selalu aktif, inovatif dan, di dalam Alkitab, bahkan berubah pikiran ketika dia menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk memunahkan ras manusia dalam peristiwa Air Bah. Ada aspek mistik Plato yang sangat menyenangkan hati kaum monoteis. Bentuk-bentuk suci Plato bukanlah realitas yang ada "di luar sana", melainkan bisa dijumpai di dalam din. Dalam dialog dramatiknya, Symposium, Plato memperlihatkan betapa kecintaan pada tubuh yang cantik bisa disucikan dan ditransformasikan menjadi kontemplasi ekstatik (theoria) tentang Keindahan ideal. Dalam naskah itu dia membuat Diotima, mentor Sokrates, berbicara bahwa Keindahan adalah unik, abadi, dan mutlak, tidak sama dengan apa pun yang pernah kita alami di dunia ini:
Baca Juga: Penemuan artefakUFO dan alien di Guanajuato
Keindahan ini pertama-tama adalah abadi; ia tidak pernah diwujudkan maupun dimatikan; tak mengalami pasang surut; kemudian ia bukan indah sebagian dan jelek sebagian, bukan indah pada satu saat dan jelek pada saat lain, bukan indah dalam kaitannya dengan hal ini dan jelek dengan hal itu, tidak beraneka menurut keragaman pemerhatinya; tidak pula keindahan ini akan tampil di dalam imajinasi seperti kecantikan seraut wajah atau tangan atau sesuatu yang bersifat jasadiah, atau seperti keindahan sebuah pemikiran atau ilmu pengetahuan, atau seperti keindahan yang bersemayam di dalam sesuatu di luar dirinya sendiri, apakah itu makhluk hidup atau bumi atau langit atau apa pun lainnya; dia akan melihatnya sebagai yang absolut, ada sendirian di dalam dirinya, unik, abadi
Pendek kata, gagasannya tentang Keindahan memiliki banyak kesamaan dengan apa yang oleh kaum teistik disebut "Tuhan". Meski sedemikian transenden, ide-ide seperti ini dapat dijumpai dalam pikiran manusia. Dalam era modern, kita memandang berpikir sebagai sebuah aktivitas, sebagai sesuatu yang kita kerjakan. Plato menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi pada akal: objek-objek pikiran merupakan realitas yang aktif di dalam akal manusia yang merenungkannya. Seperti Sokrates, dia memandang pemikiran sebagai proses mengingat kembali (recollection), pemahaman sesuatu yang pernah kita ketahui, namun telah terlupa. Karena manusia merupakan kesucian yang tercampak, bentuk-bentuk alam ilahiah ada dalam diri mereka dan bisa "disentuh" oleh nalar, yang bukan sekadar aktivitas rasional atau otak melainkan sebuah cerapan intuitif akan realitas abadi yang ada dalam diri kita. Gagasan ini akan sangat berpengaruh terhadap kaum mistik dalam ketiga agama monoteis.
Plato percaya bahwa alam semesta pada dasarnya rasional. Ini adalah mitos atau konsepsi imajiner lain tentang realitas. Aristoteles (384-322 SM) mengambil langkah lebih jauh. Dia adalah orang pertama yang mengapresiasi arti penting penalaran logis, basis semua ilmu pengetahuan, dan yakin bahwa adalah mungkin bagi kita untuk mencapai pengertian tentang alam semesta dengan cara menerapkan metode ini. Selain mengupayakan pemahaman teoretis tentang kebenaran dalam empat belas risalah yang dikenal sebagai Metaphysics (istilah yang diciptakan oleh editornya, yang menempatkan urutan risalah ini "sesudah Physics": meta ta physika), dia juga mempelajari fisika teoretis dan biologi empiris. Meskipun demikian, dia memiliki kesantunan intelektual yang besar, bersikeras bahwa tak seorang pun mampu mencapai konsepsi yang memadai tentang kebenaran, tetapi setiap orang bisa memberikan sumbangsih kecil terhadap pemahaman kolektif manusia. Banyak kontroversi mengenai penilaiannya terhadap karya Plato. Dia tampaknya secara temperamental menentang pandangan Plato mengenai transendensi bentukbentuk, menolak gagasan bahwa bentuk-bentuk itu mempunyai eksistensi pendahulu yang independen. Aristoteles berpendapat bahwa bentuk-bentuk itu hanya memiliki realitas sebagaimana keberadaannya di dunia material konkret kita ini.
Meski pendekatannya begitu membumi dan perhatiannya besar kepada fakta ilmiah, Aristoteles memiliki pemahaman yang tajam tentang hakikat dan arti penting agama dan mitologi. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam berbagai misteri agama tidak perlu mempelajari fakta apa pun "kecuali mengalami emosi dan disposisi tertentu."35Inilah dasar dari teori sastranya yang terkenal bahwa tragedi mengakibatkan purifikasi (katharsis) rasa takut dan iba yang berujung pada pengalaman kelahiran kembali. Trageditragedi Yunani, yang pada awalnya merupakan bagian dari festival keagamaan, tidak mesti menghadirkan kisah faktual peristiwaperistiwa sejarah tetapi berupaya mengilhami kebenaran yang lebih serius. Bahkan sejarah lebih remeh daripada puisi dan mitos: "Yang satu menguraikan apa yang telah terjadi, yang lainnya apa yang mungkin terjadi. Karena itu, puisi adalah sesuatu yang lebih serius dan filosofis daripada sejarah; karena puisi berbicara tentang apa yang universal, sedangkan sejarah apa yang partikular."36 Mungkin atau tidak mungkin ada seorang Achilles atau Oedipus historis, tetapi fakta-fakta kehidupan mereka tidak relevan dengan karakter yang kita saksikan dalam Homer dan Sophocles, yang mengekspresikan kebenaran yang berbeda tetapi lebih mendalam tentang kondisi manusia. Uraian Aristoteles tentang katharsis tragedi merupakan presentasi filosofis atas kebenaran yang telah dipahami Homo religiosus secara intuitif: presentasi simbolis, mitikal, dan ritual atas peristiwa-peristiwa yang tak tertanggungkan dalam kehidupan seharihari dapat menebus dan mentransformasikannya menjadi sesuatu yang murni dan bahkan menyenangkan

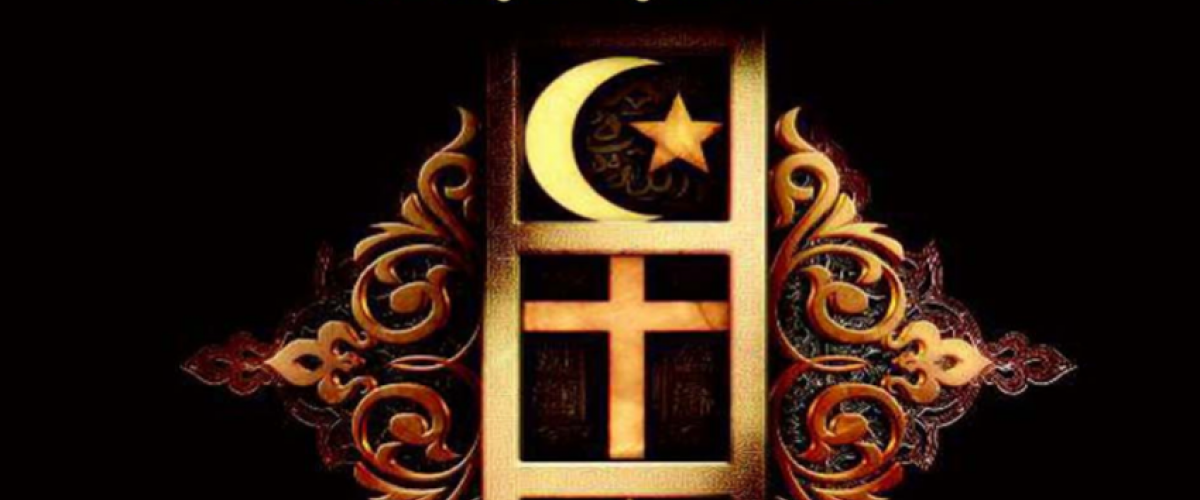














Comments (0)